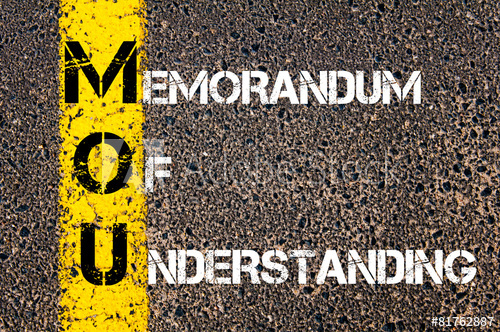Hadiah itu sunnah Nabi –shallallahu `alaihi wa sallam. Ia tanda cinta, penumbuh keakraban, dan penyubur kasih-sayang. Hadiah mendekatkan yang jauh, menyambung yang terputus, bahkan menjadi penembus hati agar menerima dakwah. Hadiah dan pemberian suka rela juga salah satu bentuk takaful (saling meringankan) dan ta`awun (tolong-menolong).
Rasulullah –shallallahu `alaihi wa sallam- mendorong aktifitas saling memberi hadiah. Beliau berpesan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah –radliyallahu `anhu:
تَهَادُوا تَحَابُّوا
“Saling memberi hadiahlah (agar) kalian saling mencinta”. (Hadits ini dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih Al Adab al Mufrad oleh Imam al Bukhari, Bab Qabulu al Hadiyyah).
Anjuran Rasulullah ini oleh para sahabat ditanamkan pada anak-anak mereka, di antaranya oleh Anas yang mengatakan:
يَا بُنَيَّ تَبَاذَلُوْا بَيْنَكُمْ فَإِنَّهُ أَوَدُّ لِمَا بَيْنَكُمْ
“Nak, saling memberilah di antara kalian, karena yang demikian paling kuat menumbuhkan kasih sayang diantara kalian” (riwayat ini oleh Al Albani dikatakan shahih al isnad dalam Shahih Al Adab al Mufrad)
Dijumpai banyak dalil yang mendorong agar kaum muslimin saling memberi hadiah (tahadi), saling memberi (tabadzul), saling meringankan (takaful), saling kerja sama (ta`awun) dan sebagainya.
Ajaran nabawi ini direspon dengan baik oleh kaum muslimin. Banyak sekolah-sekolah yang ingin menyemai cinta dan kasih sayang dalam hati para peserta didiknya, menjauhkan sifat dan perilaku hubungan sosial yang negatif dengan menyelenggarakan kegiatan ‘saling memberi hadiah’. Demikian pula dijumpai komunitas-komunitas yang ingin mengeratkan ukhuwah diantara mereka, juga melakukan hal yang sama.
Tapi, para praktisi ‘sunnah nabi’ itu (sunnah saling memberi hadiah) merasakan sedikit galau. Pasalnya, dijumpai pandangan yang mengatakan bahwa praktik itu merupakan mu`awadlah (tukar-menukar) dan mengandung gharar. Padahal, dalam praktik mu`awadlah (seperti jual beli, sewa) harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakpastian).
Mendudukkan Masalah
Saling memberi hadiah dalam format kegiatan di sekolah-sekolah atau komunitas biasanya dinamai dengan istilah tukar-menukar hadiah. Penamaan tukar-menukar hadiah, mendorong munculnya anggapan bahwa substansi praktik itu adalah tukar-menukar (mu`awadlah). Karena pertukaran, maka diantara syarat yang harus dipenuhi adalah syafafiyah (transparansi) dan mu`ayyanah (tertentu, spesifik).
Syarat-syarat itu tidak terpenuhi dalam praktik pertukaran hadiah, apalagi bila hadiah-hadiah yang dipertukarkan itu dibungkus dalam kado. Praktis, peserta kegiatan tidak tahu-menahu ‘apa yang dipertukarkan’. Akibatnya, banyak yang merasa kecewa saat mendapati hadiah yang diterima tak sesuai dengan harapan.
Pandangan lain, karena kegiatan pertukaran hadiah itu dilakukan dengan undian, ada yang mensinyalir bahwa yang demikian termasuk qimar (judi yang spekulatif). Semua peserta dianggap berspekulasi akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan melalui undian itu. Dan sekali lagi, ada yang kecewa bila tidak mendapat apa yang diharapkan serta merasa kalah.
Tapi, ada yang melihat pada kata ‘hadiah’. Ini hadiah, pemberian yang bersifat sukarela. Karena pemberian sukarela, maka tergolong tabarru` yang bersifat sosial, bukan bisnis. Tabarru` beda dengan mu`awadlat. Bila dalam mu`awadlat tidak boleh ada gharar, kecuali gharar yang sedikit, maka dalam tabarru` tidak mengapa ada gharar. Sehingga dikenal dalam madzhab Malikiyah kaidah: Al Ghararu fi `uqudi al mu`awadlat duuna al tabarru`aat, gharar (yang berdampak pada hukum) itu berlaku dalam akad pertukaran, dan tidak berlaku dalam tabarru`at (sosial dan kebajikan). Sehingga bila ada sumbangan atau pemberian suka rela yang ada dalam bungkusan, dan tidak diketahui oleh penerima, diperbolehkan.
Mu`awadlat yang tergolong akad bisnis dilakukan untuk mencari laba dan keuntungan. Dan dalam judi, orang berspekulasi dan berharap dialah yang menang. Sedangkan dalam tabarru`, tidak ada niatan mencari untung dan tidak ada dalam benak mereka istilah ‘menang’ seperti dalam judi.
Mendudukkan Substansi
Diriwayatkan dari Abu Musa al Asy`ari –radliyallahu `anhu– beliau berkata, bahwa Rasulullah –shallallahu `alaihi wa sallam– bersabda, “Sesungguhnya keluarga Asy`ariyyin, jika mereka berperang atau keluarga mereka kekurangan makan di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain, kemudian meletakkan di sebuah nampan lalu membaginya sama rata. Mereka termasuk saya, dan saya juga termasuk mereka” (HR. Bukhari dalam Bab Syirkah fi Al Tha`am wa al Nahdi wa al Urudl; Muslim dalam Bab Min Fadlail Al Asy`ariyyin)
Riwayat di atas menggambarkan praktik ta`awun jama`i (tolong-menolong secara kolektif dan saling memberi), untuk menutupi kebutuhan bersama. Inilah tabarru` (sedekah) yang tidak mengikat dan tidak ada penetapan kadar tertentu. Karena tujuan utama praktik itu adalah ta`awun dan takaful serta kebajikan, bukan laba atau bisnis, maka tak terfikir oleh mereka adanya gharar, riba, atau judi.
Ibnu Hajar –rahimahullah– menyebutkan dalam Fathu al Bari, “Boleh menghibahkan yang majhul (tak tertentu, samar) dan keutamaan itsar (mengutamakan orang lain) serta membantu”. Padahal dipastikan diantara mereka ada yang memberi sedikit dan mendapat bagian lebih banyak dari yang ia berikan atau sebaliknya. Dengan demikian, niat tolong-menolong dan kebajikan membolehkan apa yang tidak dibolehkan dalam praktik mu`awadlat (tukar-menukar).
Riwayat lain menyebutkan bahwa Jabir bin Abdullah –radliyallahu `anhuma– berkata, bahwa Rasulullah –shallallahu `alaihi wa sallam– mengirim 300 orang pasukan menuju kawasan pesisir. Rasulullah mengangkat Abu Ubaidah bin al Jarrah sebagai pemimpin mereka. Kata Jabir, “Kami berangkat hingga di perjalanan habislah bekal. Abu Ubaidah memerintahkan semua pasukan mengumpulkan bekal masing-masing. Bekalku, kata Jabir, adalah kurma. Tiap hari kami memakannya sedikit demi sedikit hingga habis. Kami mendapati satu kurma satu kurma….(HR. Bukhari dalam Bab Syirkah fi Al Tha`am wa al Nahdi wa al Urudl)
Praktik yang diprakarsai oleh Abu Ubaidah di atas adalah bentuk takaful dan ta`awun, dimana masing-masing prajurit mengumpulkan apa yang dimiliki, sedikit atau banyak. Kemudian kumpulan makanan itu dibagi kepada semua prajurit. Dalam riwayat itu tidak ada diskusi tentang gharar, riba, atau judi yang dianggap merusak akad mu`awadlah. Kata Al Baltaji dalam Uqud al Ta`min, masalah ini bukan tergolong bisnis atau laba, tapi saling meringankan dan saling membantu menghadapi kekurangan makanan. Dan dipastikan diantara mereka akan mendapat jatah makan lebih banyak atau lebih sedikit dari yang diberikan.
Dua riwayat itu dan beberapa dalil lain tentang hadiah, menunjukkan bahwa saling memberi hadiah atau saling memberi didasarkan pada prinsip tabarru` (kebajikan, sosial). Dan dalam tabarru`, takaful, ta`awun, tahadi (saling memberi hadiah), tabadzul (saling memberi) tidak ada syarat bahwa masing-masing harus memberi sejumlah yang sama atau berbeda. Sebagaimana, apa yang didapatkan oleh masing-masing peserta apakah lebih banyak atau lebih sedikit dari yang diberikan, juga tidak menjadi syarat bagi sahnya praktik atau akad tabarru`.
Menurut Suwailim yang dikutip Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al `Umrani dalam Al Uqud Al Maaliyah Al Murakkabah menyebutkan, bahwa al tabarru` al mutabadil (saling memberi) tak dilarang meskipun dalam format mu`awadlat (tukar-menukar). Mengapa? Karena masing-masing pihak tidak bermaksud mendapat laba atau ganti lebih baik. Tujuan mereka adalah ta`awun. Boleh jadi diantara mereka ada yang mendapat lebih atau kurang dari yang diberikan, tapi semua saling ridha dalam persamaan berkontribusi.
Simpulan & Modifikasi
Setelah mencermati dalil-dalil dan pandangan ulama di atas, bahwa terhadap praktik tukar-menukar hadiah, secara substantif adalah tabarru`, bukan mua`wadlat, meskipun dengan nama mu`awadlat atau dalam format tukar-menukar. Karena al `ibratu bi al maqashidi wa al ma`ani laa bi al faadhi wa al mabani (yang jadi patokan adalah maksud dan makna dari aktifitas itu, bukan redaksi konstruksi (kata/kalimat yang digunakan). Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi memberi hadiah yang bersifat tabarru`, bukan redaksi tukar-menukar.
Praktik kegiatan tukar menukar hadiah sesungguhnya bertujuan sosial dan ukhuwah, bukan bisnis untuk mencari keuntungan. Kegiatan semisal itu yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah, komunitas-komunitas adalah bertujuan untuk ta`lifu al qulub (merekatkan hati) agar ukhuwah menjadi kokoh, atau menghilangkan benih-benih tanazu` (konflik).
Adapun undian yang digunakan dalam praktik tabadzul hadaya hanya sebagai sarana untuk membagi. Bukan untuk takassub dan jam`i al maal (memperoleh pendapatan dan mengumpulkan harta), layaknya yang dipraktikkan dalam judi. Semua yang ikut serta akan mendapatkan bagian, sebab substansinya adalah saling memberi dan saling mendapatkan, bukan untung-untungan oleh salah satu atau beberapa peserta. Undian dalam praktik ini hanya cara membagi, sebagaimana pembagian langsung yang dilakukan oleh pimpinan, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dalam riwayat di atas juga sebagai cara membagi. Intinya adalah semua mendapat bagian.
Meskipun kegiatan tukar-menukar hadiah secara substansi adalah tabarru`, dan tidak mengapa adanya gharar, dan diundi untuk membagi bagian masing-masing, tapi guna menghindari ikhtilaf, ada baiknya diperhatikan hal-hal berikut:
- Semua peserta dipahamkan dan memahami bahwa kegiatan tukar-menukar adalah saling memberi hadiah yang bersifat suka rela dan kebajikan (tabarru`).
- Memastikan bahwa niat masing-masing peserta adalah memberi, bukan untuk mendapat keuntungan (laba) atau menang undian. Agar dipastikan bahwa tujuan utama kegiatan itu adalah ta`liful qulub (mengeratkan hati), menguatkan ukhuwah, atau ta`awun dan takaful.
- Diperlukan motivasi kepada peserta untuk berusaha memberi yang terbaik untuk saudaranya sesuai dengan kemampuannya.
- Lebih baik tidak menggunakan istilah ‘tukar-menukar hadiah’, tapi menggunakan istilah tahadi, seperti yang disebutkan dalam hadits yang berarti saling memberi hadiah, atau istilah tabadzul seperti yang dipraktikkan oleh Anas –radliyallahu `anhu- yang juga bermakna saling memberi (tabadzul hadaya).
- Bila cara undian mengesankan praktik judi, bisa diganti dengan cara seorang guru, atau panitia, atau pimpinan yang membagi untuk semua peserta, seperti yang dipraktikkan oleh Ubaidah bin al Jarrah.
Wallahu a`lam bisshawab
Malang, 25 Januari 2018
Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
KPS Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
www.tazkiyatuna.com